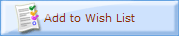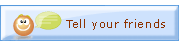|
|
Sinopsis Buku: Kata “tempurung” dalam kumpulan sajak karya dua penyair ini dilepaskan dari segala macam asumsi seperti dikenal dalam amsal “seperti katak dalam tempurung”. Dua penyair tadi sama-sama menulis puisi dengan judul sama dan berusaha membuat tafsir baru. Resensi Buku:
     TEMPURUNG TENGKURAP DALAM TAFSIRAN RUANG MAKNA TEMPURUNG TENGKURAP DALAM TAFSIRAN RUANG MAKNA oleh: alizar tanjung Menelaah karya sastra, membuka kepada isi. Dikelupas kulitnya, diambil sari buahnya. Kulitnya menjadi jalan kepada jantungnya. Agaknya ini yang menjadi perhatian saya ketika membaca sajak-sajak Mahatma Muhammad dan Yori Kayama. Polemik tentang mencari kebenaran terselubung saya menamakan dengan kebenaran abstrak, bergantung kepada setiap pembaca, kritikus, esais yang menafsirkannya, baik penafsiran dengan tek terpisah, maupun dengan interteks atau sama sekali mencari kekosongan. Dan akhirnya berbuah dengan suatu jawaban “tempat dimana Tuhan tiada” kata Orhan Pamuk. Yang ada hanya ambiguitas terhadap penafsiran suatu peristiwa dan karya. Hingga adanya sebuah penjara panjang yang saling mengekang mana yang mesti masuk penjara penulis budak-budak puisi, cerpen, novel dan mana mesti yang masuk penjara pengarang yang memelihara puisi, cerpen, novel yang memiliki ruang bebas dari pengaruh jeruji. Akhirnya penulis tidak akan terlepas dari sebagai pengikut atau penyembah teks. Sedangkan mengarang merupakan ranah penemuan dan pencarian terus-menerus. Pencarian dan penemuan bagian sari dari dirinya dan jiwa-jiwa di luar dirinya. Jiwa-jiwa hutan, batu, air, bumi, tanah, anak cucu Adam. Mengarang membongkar jiwa-jiwa yang gelisah. Jiwa-jiwa gelisah itu bermunculan ketika peristiwa-peristiwa terus berhimpitan dalam bentuk perenungan-perenungan. Perenungan “memelihara luka” kata Damhuri Muhammad (Subhan, 2011). Lalu persoalan hidup dalam tubuh pengarang bukan lagi persoalan “apa ini”, “apa itu”. Persoalan hidup bagi pengarang adalah persoalan “kenapa”, “bagaimana”, “kemana akan”. Seperti halnya kerja akal. “Manusia itu hewan yang berakal.” Tidak salah memang kalimat yang tidak asing lagi di telinga kita. Pada dasarnya manusia memiliki sifat hewani. Sifat hewani tidak memikirkan apa yang telah ia perbuat. Sifat hewani melihat dengan mata brutal. Sedangkan manusia diberikan akal yang membedakan dengan hewan. Artinya manusia bukanlah hewan. Akal selalu mencari jalan kebenaran. Sebab itu sifat akal selalu ingin membuang sifat kehewanan dalam dasar fitrah manusia. Pengarang penyair, prosais seperti halnya penyair “Tempung Tengkurap” menimbulkan pertanyaaan. Benarkah sebenarnya katak benar-benar merasakan bebas di tempurung tengkurap atau sebenarnya akal-akalan orang yang menemukan ambiguitas ketika harus menempatkan katak sebagai permisalan? Hal ini kemudian menjadi landasan bagi penyairnya untuk keluar dari ambiguitas itu. Tempurung Tengkurap Mahatma dan Tempurung Tengkurap Yori Kayama lebih tepat dikatakan terhadap kedalaman menyelami diri dan hal-hal yang berhubungan diri. Entah itu persoalan rasa atau perabaan akan sesuatu. Kedalaman menyelami diri itu hendak melepaskan dari segala sesuatu dari pengulangan masa lalu. Penyair hendak membenrontak, masa sekarang dan masa lalu mesti hendaklah berjenjang. Sehingga sampai kepada pencapaian tertinggi. ketika harus menetap/ berbisik di bayang malam/ makin larut/ aku takut... menetap pada ratap/ tempurung tengkurap// (tempurung tengkurap oleh Mahatma Muhammad) Pengarang menempatkan tempurung tengkurap pada tempat yang butuh penerangan. Penerangan itu titik terang dari keterkungkungan. Tempurung Tengkurap menjadi simbol bagi keberadaan menyusun dan menghayati partikel-partikel kehidupan. Hal ini tentunya dapat dilihat dari filosofi tempurung itu sendiri. Tempurung itu sendiri adalah batok kelapa, isinya berguna, tempurungnya bahkan jauh lebih berguna. Sedangkan tempurung tengkurap bagi Mahatma dan Yori Kayama adalah eksistensi keberadaan tempurung itu sendiri bagi kehidupan ini. Bagi kehidupan seratus puisi yang termuat dalam buku “Tempung tengkurap”. Tempat di mana bahwa hidup tak akan lari dari pencarian diri. Tengkurap itu sendiri tertelungkup, saya memaknai ada sesuatu yang rahasia yang mesti dibongkar. Bahwa sifat dasar manusia suka mengintip yang tersembunyi. Artinya ada segala sesuatu dari balik yang nampak. Dengan kata lain jangan terkungkung dengan yang kasat mata. Tentunya dalam hal ini yang saya maksud bukan sekedar hubungan “katak” dengan “tempurung tengkurap”. Saya lebih mengatakan antara pencarian sesuatu “entah apa” bagi pengarang dan pembenaman terhadap pondasi masa lalu. engkau selalu berjaga dan menjaga aku/ dalam dua buah tikungan sedikit ragu// (angin yang berbisik). ketika kita membuka ayat Tuhan kita akan bertemu dengan kata fujuraha dan wataqwaha. Pencarian akan “entah apa” adalah atas gelisah yang dipelihara penyair “tempurung tengkurap”. Mengapa waktu berbenam/ kita berkemas/ bergegas cemas/mengapa waktu menjauh/ kita bersimpuh/tergugu ricuh... (pantai parangtritis). Pencarian akan sesuatu pengarang semakin berwujud dalam mimpi kita senantiasa gelisah menanti wujud/ sehingga kita kita merayu mengharapnya datang/ karena seribu pertanyaan telah membakar diri/ketika seribu jawaban bersembunyi// mimpi kita seperti jauh dari dalam diri/ sebuah kekosongan yang wujud walau tanpa ada/... (mimpi kita absurd). Pencarian yang mewujudkan “entah” menjadi “asal”. Pada halaman rumah telah terhampar kubur, sayang/ mengembangkan pekarangan dengan bunga kematian/ (berbagi kubur). Hidup akhirnya menghisap sebatang rokok, meminum segelas kopi, membaca negeri. Interteks zig-zag yang saya lakukan terhadap puisi-puisi Mahatma menemukan jalan lama dan jalan baru pada satu rumah yang berbeda. Perenungan masa lalu, masa sekarang, masa depan disimbolkan dengan sebatang rokok, segelas kopi. Pada puisi “cerita sama”: entah bagaimana angin mengabarkan tapi aku yakin kau tahu/bahwa aku jengah dengan segala rutinitas. mencium aroma sama/ melakoni cerita berulang pada punggung-punggung yang tak beda/....aku/ yakin kau purapura tak tahu/// kita Mahatma kembali memulangkan ke asal. Kita akan berpulang kepada persoalan yang itu ke itu. Bagi yang tidak jelimet, terjebak dalam lingkaran yang sama. Hidup menjadi roda pedati. Kadang di atas kadang terlindas. Sepertinya halnya puisi “sandiwara”: tanpa sebab, aku menonton sandiwara/ panggung terbuka/ aktor aktris bersolek di lampulampunya/dalam tatapan diam/ kau terdampar entah dimana//. Di sisi lain, pada puisi Mahatma saya menemukan kebaruan pada puisi “afrizal malna” dan “patgulipat berlipatlipat”. Kebaruan yang menurut saya cukup menemukan keberadaan apa yang dicari sebagai sebuah teks dan pelafazan puisi. “afrizal malna” dan “patgulipat berlipatlipat” menawarkan angin segar. Membaca dua puisi ini melagukan dua puisi. Membacanya saya harus melagukannya, hingga baru saya dapat menafsirkan apa yang hendak ingin dimakan dua puisi ini. Lihat lirik “afrizal malna”: botak gunduk botak gundul botak gundul penuh isi botak gundul/berpuisi/botak gundul botak gundul botak gundul tak ndul tak ndul tak ndul/ isi puisi/ tak botak ndul gundul tak botak ndul gundul penuh isi/ ndul gundul tak botak ndul tak botak berpuisi///. Membaca puisi ini membaca Afrizal Malna, maestro puisi dan. Sehingga bagi puisi ini Afrizal Malna adalah perbedaan dengan sesuatu yang usang dan yang baru. Bukan lagi sekedar persoalan siapa yang memangku nama, lebih daripada itu soal pembaruan yang ingin ditawarkan dalam perpuisian.. Pada puisi “patgulipat berlipatlipat”: patgulipat berlipatlipat penjahat ditangkap penjahat/penjahat dirawat penjahat penjahat mengajar penjahat/patgulipat berlipatlipat ada istilah teman dekat/ berbondongbondong masuk lapas jangan kuatir tak bisa lepas/ada uang sekali kibas boleh bebas menarik nafas/...persamaan bunyi dan penekanan bunyi menjadi penekanan apa yang hendak dituju oleh pengarang. Sehingga persamaan bunyi muncul dalam bentuk melagukan puisi. Akhirnya untuk Mahatma, saya berujar mengarang mengelupas isi peristiwa, seperti halnya filsafat melakukan analisis mencari kebenaran abstrak. Mengarang membutuhkan daya kritis yang tajam terhadap suatu peristiwa, sedangkan kritis adalah bagian dari dunia filsafat. Mengarang memancarkan fakta-fakta terselubung, dalam makna lain di mana sastra tidak akan terlepas dari fakta. Sedangkan filsafat selalu mencari kebenaran-kebenaran yang terselubung. Lain halnya dengan Yori Kayama dalam puisi “tempurung tengkurap” mengakar sepanjang jalan, melenyapkan kesedihan di ruas-ruas risau/ bergulung menari riang sepanjang musim persinggahan/ pada punggung telah tengkurap badan sepenggal//. Bukankah pencarian akan berbuntut dengan pencarian lainnya, setelah pencarian diri sendiri akan berbuntut pada pencarian diri orang lain. Setelah pencarian akan sesuatu akan berbuntut dengan pencarian di balik sesuatu. Yori Kayama mengatakan hidup mesti mengakar sepanjang jalan, dalam hal saya diingatkan kepada Taufiq Ismail menggapai ke langit mengakar ke bumi. Pada dasarnya kembali akan berwujud kepada kebenaran absolut, yaitu kebenaran Tuhan. Mengakar sepanjang jalanan/Pecah gemuruh menggigil kota/ Akar hilang belukar pun tiada/ Berjayalah sebuah kebebasa/ Penyair sendiri menyadari mengakar sepanjang jalan adalah pondasi untuk mengakar sepanjang jalanan kota. Dua dunia hidup, dunia dalam diri dan dunia di luar. Sebab kebebasan bukanlah tujuan. Kebebasan hanyalah bagian dari paradoks. Hal ini akan kembali ditemukan dalam “Aku Ingin Setetes Cahaya”. Kembali ke akar adalah untuk menunjukkan diri kita sendiri ke asal. Menariknya sajak-sajak Yori Kayama seperti halnya Mahatma menobelkan kebenaran sebagai cahaya. Habis Gelap Terbitlah Terang, ujar RA Kartini. Pasti ada sesuatu yang menyimpan kebenaran. Simbol tubuh yang digunakan Yori Kayama “akar/pembuluh tubuh”, “mata”, “hidung”, “bibir”, “telinga”, “tangan”, “kaki” semakin mendekatkan pengarang kepada apa yang ia cari. Kegalauan dan kegelisahan pengarang menampakkan wujud. ada yang didengar lain di musim hujan kota jakarta/ bunga-bunga mencipta nasibnya sendiri di perempatan jalan/ langit mencari takdirnya masing-masing/ segala yang iba telah dicairkan lewat tetes air/...(Hujan Kota Jakarta) Parodi. Pelakon hendaknya menyadari parodi. Parodi itu bermain di sekitar-sekitar itu juga. Sebab kegalauan dengan kecemasan mesti diselesaikan dengan ketenangan. Nah, inilah yang menari-nari dari puisi-puisi Mahatma dan Yori Kayama. Seperti halnya Mahatma, Yori Kayama menemukan persoalan yang sama dalam “Lompatan” hal ini ditemukan pula dalam puisi “cerita sama” milik Mahatma. Kalaulah tidak cermat menjalani hidup akhirnya akan masuk dalam putaran yang sama. perjalanan penting hanyalah membuka beberapa ingatan lama. Ah, demikian sedikit apresiasi saya yang lebih saya fokuskan kepada tafsiran isi, tentulah kajian ini belum seperti apa yang ada dalam kegelisahan-kegelisahan pengarangnya. Untuk persoalan medium bahasa yang digunakan oleh pengarang, lain kali akan menjadi kajian lanjutan untuk buku puisi “tempurung tengkurap”. Seperti kata Budi Darma, karangan itu memiliki dua mata yang saling mengikat, adakala bagian yang tampak––diksi, tipografi–– yang begitu mengikat karangan, adakala kita diminta untuk membaca apa yang tidak dituliskan oleh pengarangnya sendiri. n Padang, November 2011  Add your review for this book! Add your review for this book!
Buku Sejenis Lainnya:
 Advertisement |
 |
Hello.
 or or

|
 My BukaBuku | My BukaBuku |
 Cart | Cart |
 Help Help
|